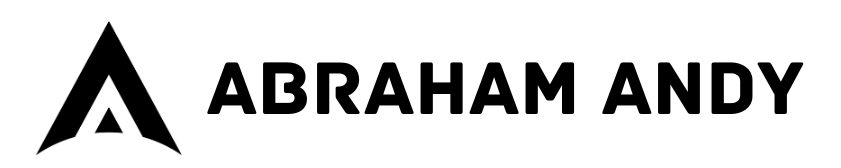Aku duduk diam.
Dari balik jendela, aku melihat hujan mengguyur pelan.
Butiran air menabrak kaca, meninggalkan jejak tipis, lalu jatuh tanpa suara.
Sederhana. Alami. Tidak terburu-buru.
Tidak seperti kita — manusia yang gemar menggiring diri sendiri ke lomba lari yang bahkan tak pernah ada panitianya.
Katanya, waktu itu adil.
Semua orang dapat jatah 24 jam sehari.
Tapi kenapa ada yang bisa menggunakannya untuk membangun kerajaan bisnis, belajar tiga bahasa asing, sambil tetap sempat ngopi dan update IG story,
sedangkan aku… baru ngeh kalau hari sudah malam ketika security kantor mengetuk pintu ruangan sambil berkata:
“Masih lanjut, Pak?”
Fenomena ini bukan soal kemampuan mengatur jadwal.
Ini tentang bagaimana kita mempersepsi waktu —
sebuah entitas (atau apalah sebutannya) tak kasat mata,
yang perlahan tapi pasti, mempermainkan rasa percaya diri kita.
Saat kita bahagia, waktu terasa melaju secepat motor bapak-bapak di jalanan sepi.
Saat kita gelisah, waktu lebih lambat dari buffering YouTube waktu nonton video Full HD pakai sinyal 3G.
Lucunya, perubahan kecepatan ini bukan salah waktu.
Ini murni hasil dari bias kognitif kita sendiri —
lebih tepatnya, otak kita yang punya harapan tak realistis bahwa waktu akan selalu “terasa pas”,
sejalan dengan perasaan dan agenda pribadi kita.
Kita ingin waktu melambat saat menikmati momen, dan mempercepat saat menunggu.
Tapi waktu tidak peduli.
Sebenarnya, waktu itu seperti algoritma media sosial:
tidak pernah berubah, tapi selalu sukses membuat kita merasa kurang.
Ia tidak berkompromi. Tapi kitalah yang terus mengkompromikan perasaan kita —
menyalahkan diri sendiri saat satu jam terasa terlalu cepat di hari libur,
atau terlalu lambat saat menunggu balasan pesan penting.
Kalau dipikir-pikir, waktu itu seperti teman lama yang toxic:
- Selalu ada.
- Tapi hadirnya bikin kita mempertanyakan diri sendiri.
- Tidak pernah minta maaf, tapi kita yang merasa salah.
- Dan ironisnya, kita tetap terus menjadikan waktu sebagai patokan utama
dalam menilai “berarti tidaknya” hidup kita.
Lihatlah pohon di luar sana.
Ia bertumbuh tanpa tekanan.
Ia tidak takut kalau pohon lain lebih cepat berbuah.
Ia tidak stres kalau angin musim ini datang lebih telat dari biasanya.
Pohon tahu:
ada musimnya untuk berbunga, ada musimnya untuk meranggas.
Tidak semua proses harus kelihatan cantik untuk dianggap sah.
Bandingkan dengan kita:
Kita pakai jam tangan mahal, aplikasi to-do list, kalender digital — semua untuk “mengendalikan” waktu.
Padahal, kadang jam tangan pun mati. Kadang jadwal pun berantakan.
Dan anehnya, kita malah marah ke diri sendiri,
bukan ke fakta bahwa hidup memang tidak tunduk pada template buatan Google Calendar.
Mari jujur.
Seringkali, yang kita takuti bukan kehabisan waktu.
Yang kita takutkan adalah kehabisan peluang untuk merasa berarti.
Waktu menjadi cermin yang brutal:
- Apakah aku sudah cukup sukses?
- Apakah aku sudah cukup berguna?
- Apakah aku sudah cukup “nyampe” di standar sosial?
Padahal, siapa yang membuat standar itu?
Kita sendiri?
Atau orang yang bahkan tidak peduli kalau kita besok hilang dari radar?
Kita terlalu sering mengukur hidup seperti kita mengukur baterai HP:
- 100% = Produktif
- 50% = Mulai panik
- 10% = Overthinking & existential crisis
Ironinya, saat kita panik mengejar waktu,
kita justru kehilangan momen-momen kecil yang mestinya kita nikmati.
Jadi, kalau hari ini kamu merasa terlambat, tertinggal,
atau “gagal” memenuhi timeline buatan dunia ini,
santai saja.
Kamu bukan peserta lomba.
Kamu bukan target market motivator MLM yang bilang:
“Start your hustle today!”
Kamu manusia — yang kadang maju, kadang diam,
kadang salah jalan, kadang istirahat.
Waktu?
Dia tetap jalan.
- Bahkan saat kamu diam.
- Bahkan saat kamu menangis di kamar mandi sambil nonton Comedy Sunday.
- Bahkan saat kamu menertawakan absurditas ini sambil nyemil gorengan di Warkop Pitu Likur.
Kalau mau merasa sedikit lega:
ingat, jam dinding rusak pun tetap benar dua kali sehari.
Jadi kalau kamu merasa gagal,
mungkin kamu cuma lagi pas sama waktu di sisi bumi yang lain.
Waktu tidak kejam.
Dia hanya konsisten.
Yang kadang kejam, adalah ekspektasi kita sendiri terhadapnya.
Jadi, kalau hari ini kamu merasa tertinggal,
ingat:
bahkan jam dinding rusak pun benar dua kali sehari.
Berhenti mengejar waktu.
Mulai berdamai dengan dirimu.
Karena pada akhirnya,
momen yang kamu nikmati itulah yang membuat hidupmu utuh.